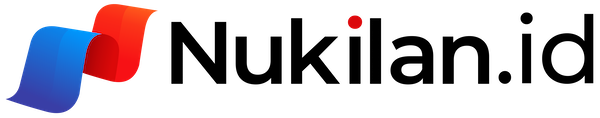Nukilan.id – Perang antara rakyat Aceh melawan Belanda yang terjadi sepanjang 1873-1912 menyisakan banyak cerita sejarah. Salah satunya, perlawanan yang dilakukan perempuan. Era itu memunculkan para pejuang perempuan tangguh, seperti Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Pocut Meuligo, Pocut Baren Biheue, Tengku Fakinah, dan Inen Mayak Teri.
Menurut Rosnida Sari dalam Acehnese Women: A History of Acehnese Women Leaders (2016), mereka adalah simbol kekuatan perempuan yang tumbuh dari kearifan lokal berbasis Islam.
Kearifan itu juga menguat dalam pendidikan karakter yang tergambar pada lirik-lirik do da idi. Dalam kebudayaan masyarakat Aceh, do da idi adalah syair pengantar tidur bagi anak-anak—atau peuayon aneuk dalam bahasa Aceh.
Reni Nuryanti dan Bachtiar Akob dalam Perlawanan dari Ayunan (2020) menyebut, do da idi adalah alat pewarisan semangat jihad. Lain itu, Do da idi juga menjadi terapi psikologis untuk menurunkan ketakutan dan ketegangan dalam situasi perang.
Lirik-lirik do da idi mengandung nilai jihad yang dimaksudkan sebagai perlawanan terhadap penjajah Belanda. Yusri Yusuf dan Nova Nurmayani dalam Syair Do Da Idi dan Pendidikan Karakter Keacehan (2013) menyebut, bagi masyarakat Aceh, ia merupakan senjata kultural dalam perlawanan terhadap orang kafir (kaphe).
Kemunculan do da idi tidak bisa dilepaskan dari sejarah Perang Aceh dan naskah Hikayat Prang Sabi yang menjadi inspirasinya. Anzib dalam Hikayat Prang Sabi Mendjiwai Perang Atjeh Melawan Belanda (1971) menegaskan bahwa sebagai karya sastra, Hikayat Prang Sabi punya posisi penting karena dua aspek. Ia memenuhi syarat keindahan bahasa sebagai karya sastra dan memiliki muatan pendidikan karakter.
Inspirasi Hikayat Prang Sabi
Semangat jihad fi sabilillah pertama kali menggema pascakekalahan laskar Aceh dari serdadu Belanda. Pada 24 Januari 1873, panglima militer Belanda Letnan Jenderal Jan van Swieten berhasil menduduki istana Kesultanan Aceh. Setahun kemudian pada 16 Maret 1874, Banda Aceh berubah nama menjadi Kutaradja.
Dalam kondisi Aceh yang terpuruk itulah kemudian muncul kesadaran untuk bersatu di antara kalangan ulama, ulee balang, dan rakyat. Di bawah pimpinan Imeum Lungbata selaku ulama dan Teuku Lamnga—suami pertama Cut Nyak Dhien—selaku ulee balang, tercetuslah sumpah “wajib perang sabil”.
Sumpah yang diucapkan di Aceh Besar itu lantas mendulang simpati para ulama dari wilayah lain. Lalu, muncullah Teungku Tjhik di Tiro yang didapuk masyarakat Aceh sebagai pemimpin perang sabil. Tak sendiri, Teungku Tjhik di Tiro juga disokong oleh adiknya, Teungku Tjhik Pante Kulu.
Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Imran Teuku Abdullah, Teungku Tjhik di Tiro kemudian meminta adiknya itu menggubah naskah syair yang nantinya dinamai Hikayat Prang Sabi.
Jadi, Hikayat Prang Sabi sejatinya adalah karya sastra perlawanan. Para pakar sejarah dan budaya Aceh, seperti Anzib, Ali Hasjimy, dan Anthony Reid, kemudian mengakui Teungku Tjhik Pante Kulu sebagai pengarangnya yang sah.
Sebagai karya sastra perlawanan, syair-syair Hikayat Prang Sabi amat kental dimuati nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, dan secara khusus mengajarkan tentang jihad melawan orang kafir untuk membela Islam. Orang kafir dalam konteks ini ditujukan pada penjajah Belanda.
Sebagai misal, simaklah penggalan Hikayat Prang Sabi berikut ini.
Diteungku pih neumoe sangat
(Menangislah Teungku tambah sedu)
Sajangneuh that h’ana sakri
(Sayangkan anak akan pergi)
Djak hee aneuk beuseulamat
(Berangkatlah sayang buah hatiku)
Keuloon taingat djeub-djeub hari
(Jangan lupakan gurumu ini)
Samlakoe tjut that guransang
(Muda belia sangatlah garang)
Kafee neutjang dum meugulee
(Kafir dicincang tikam berganda)
Djipagap lee kafee suwang
(Akhirnya terkepung muda pahlawan)
Muda seudang h’ana lheueh lee
(Jalan lepas sudah tiada)
Sikureueng droe kafee neutjang
(Sembilan kafir mati ditikam)
Muda sedang tak lihee
(Muda pahlawan berjuang berani)
Siplooh droe kafee njawong hilang
(Setelah sepuluh musuh dicincang)
Muda seudangreubah meugulee
(Muda belia syahid menemui Ilahi)
Hikayat Prang Sabi bukan hanya membentuk mental perlawanan terhadap Belanda, tapi juga mewujud menjadi strategi politik. Menurut Imran Teuku Abdullah, banyak pejuang Aceh yang maju ke medan perang dengan membawa potongan lirik Hikayat Prang Sabi. Potongan-potongan lirik itu kerap ditemukan pada jenazah mereka yang gugur.
Menurut Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912 (1987), lirik-lirik Hikayat Prang Sabi memang dianggap punya kekuatan spiritual dan kerap dijadikan azimat. Pasalnya, hikayat itu juga memuat ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah yang ditulis oleh ulama dan dipandang sebagai sumber karamah.
Kuatnya pengaruh Hikayat Prang Sabi mewujud pula dalam lirik do da idi yang biasa dilagukan para ibu pada saat menidurkan anaknya. Ada kemiripan di antara keduanya, terutama dalam aspek tema yang mencakup soal ketuhanan, jihad, juga harapan agar anak muda menjadi pejuang dan pembela Aceh (nanggro).
Menyanyikan do da idi dengan demikian sekaligus menjadi bentuk resiliensi dan “resistensi dari dalam” yang dilakukan perempuan Aceh.
Perlawanan dari Buaian
Do da idi adalah bentuk “resistensi sejak bayi” dan berfungsi sebagai penyampai pesan “wajib sabil” yang diperintahkan ulama. Perempuan Aceh ikut ambil bagian dalam proses pewarisan perlawanan rakyat Aceh kepada generasi penerus.
Ruth Finnegan dalam Oral Traditions and the Verbal Arts: A Guide to Research Practices (2005) menegaskan bahwa secara historis, perempuan Aceh amat mahir menyenandungkan sastra lisan. Mereka mampu memanfaatkan irama, rima, ragam bunyi, ungkapan, bahasa, simbol, dan tema yang terdapat dalam karya sastra lisan.
Pada masa Perang Aceh di paruh akhir abad ke-19, ayunan bagi masyarakat Aceh bukan sekedar sarana menidurkan bayi. Di situlah para perempuan menyenandungkan do da idi. Jadi, sambil mengayun anak, para ibu sekaligus juga mengajarkan anak-anaknya tentang keberanian melawan Belanda.
Merekayang tidak ikut maju ke medan perang, pada akhirnya mewariskan harapan kepada anak-anaknya. Dari sinilah, benih perlawanan terhadap Belanda bersemi.
Contoh dari narasi perlawanan itu seperti tergambar dalam lirik do da idi berikut ini.
Allah hai do doda idang
Seulayang blang ka putoh taloe
(Layang-layang di sawah putus tali)
Beurijang rayeuk hai muda seudang
(Cepatlah besar hai anak muda)
Tajak bantu prang bila nanggroe
(Ikut bantu berperang membela negeri)
Wahee aneuk bek taduek le
(Wahai anakku janganlah duduk kembali)
Beudoh sare bela bangsa
(Bangun berdiri bersama membela bangsa)
Bek tatakot keu darah ile
(Jangan takut meski darah harus mengalir)
Adak pih mate poma ka rela
(Sekira engkau mati, ibu merelakan)
Allah hai Po ilahonhaq
(Allah sang pencipta punya kehendak)
Gampong jarak han troh tawoe
(Kampung jauh, kita tak bisa pulang)
Adakan bulee ulon teureubang
(Seandainya punya sayap, aku akan terbang)
Mangat reujang troh u nanggro
(Supaya lekas sampai ke negeri Aceh)
Terapi Psikologis
Selain sebagai sarana pewarisan semangat jihad, do da idi juga menjadi pereduksi ketegangan, kekhawatiran, ketakutan, atau bahkan kemarahan yang dirasakan oleh seorang perempuan. Pasalnya, syair do da idi juga memuat pujian, doa, dan selawat. Itu semua adalah “cara tradisional” masyarakat Aceh untuk memunculkan ketenangan.
Sebagai misal, simaklah lirik do da idi berikut yang dikutip dari Syair Dodaidi dan Pendidikan Karakter Keacehan (2013) susunan Yusri Yusuf dan Nova Nurmayani.
Laailaahaillallaah
Kalimah thaibah keupayong page
(Kalimah thaibah payung akhirat)
Uroe tutong batee beukah
(Panasnya matahari sampai batu terbelah)
Hanco darah lam jantong hate
(Hancur darah dalam jantung hati)
Laailaahaillallaah
Kalimah thaibah beukai tamate
(Kalimah thaibah bekal kita mati)
Taduk tadong zikir keu Allah
(Duduk dan berdiri zikir kepada Allah)
Han ek ngon babah ingat lam hate
(Tak sanggup dengan mulut, ingat dalam hati)
Lirik tersebut menggambarkan situasi psikologis, sosial, dan kultural masyarakat Aceh di masa perang. Ia lazim disenandungkan oleh mereka yang kebetulan tidak ikut berperang karena harus membesarkan anak.
Meski jauh dari pertumpahan darah, kondisi lingkungan tidak serta-merta memberikan ketenangan batin. Karena itulah, perempuan Aceh melagukan lirik-lirik do da idi yang menggambarkan kegelisahan, ketegangan, ketakutan, bahkan kemarahan terhadap situasi. Mereka akhirnya mewakilkan perasaan dan pikirannya pada do da idi.
Dengan demikian, do da idi tak hanya berisi kepasrahan perempuan, tapi juga harapan kepada pertolongan Allah. Itulah alasan lirik do da idi tersebut diawali dengan kalimat Laailaahaillallaah—kesaksian bahwa tidak ada tempat berlindung, kecuali Allah.
Sebagaimana tersebut dalam Hikayat Prang Sabi, lirik do da idi juga menyuratkan bahwa keyakinan pada akhirat menjadi akhir perlawanan terhadap Belanda. Energi jihad menginspirasi untuk tetap mengangkat senjata. Ia menjadi simbol perjuangan mulia di mata Islam. Sebab dalam pandangan masyarakat Aceh, perang melawan Belanda adalah perang menegakkan agama Islam.
Heroisme jihad seperti itulah yang dilantunkan para ibu kepada anaknya dalam buaian. Meski sedang meniti maut, perempuan Aceh yakin bahwa jihad akan berakhir syahid.
Sebab itulah, H.C. Zentgraaf dalam Aceh (1983) menulis, “Tidak ada satu bangsa yang begitu bersemangat dan fanatik dalam menghadapi musuh selain bangsa Aceh dengan wanita-wanitanya yang jauh lebih unggul daripada semua bangsa lain dalam keberanian menghadapi maut.” [tirto.id]