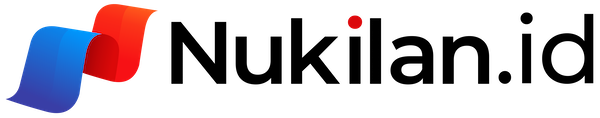*Teuku Harist Muzani
Nukilan.id – Kepastian Pilkada Aceh berlangsung di tahun ini tampaknya masih menyisakan tanda tanya. Bagaimana tidak. Bila merujuk Keputusan KIP Aceh tentang Tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 yang disahkan januari lalu, tepat tanggal 1 April 2021 adalah batas akhir penyusunan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NHPD) antara KIP dan Pemerintah Aceh.
Namun hingga tulisan ini ditulis, belum ada sinyal positif baik dari pemerintah Aceh maupun pusat bahwa Aceh pasti dapat menggelar Pilkada pada tahun 2022.
NHPD sendiri merupakan dasar bagi kepastian anggaran pelaksanaan Pilkada. Tanpa adanya kepastian anggaran, KIP tentunya tidak mampu berbuat apa apa.
Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Dr. Syamsul Bahri bahkan dengan terang terangan menyatakan pemerintah Aceh selama ini tidak membantu KIP Aceh dalam menjalankan tahapan Pilkada 2022, yang direncanakan sejak awal 2020 silam.
“Kami jujur saja. Selama ini tidak ada uang sepeser pun yang diberikan pemerintah Aceh untuk KIP Aceh,” kata Syamsul saat Audiensi yang dilakukan Muda Seudang di kantor KIP Aceh, pada Jum’at (19/3/2021). Seperti yang dilansir Nukilan.id pada Sabtu, (20/3/2021).
Baca juga: DPRA Rakor Satukan Sikap Jalankan Pilkada Aceh 2022
Kabar terakhir menyangkut Pilkada Aceh, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dijadwalkan akan mengundang seluruh elemen partai politik nasional dan partai politik lokal pada hari ini, Rabu, 24 maret 2021 dalam rangka rapat kordinasi dan penegasan sikap bersama terkait pelaksanaan Pilkada Aceh.
Pemerintah Aceh sendiri berada dalam posisi dilematis. Meski disatu sisi pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya seperti koordinasi dan komunikasi dengan pusat agar Pilkada Aceh bisa digelar sesuai jadwal yang ditetapkan KIP Aceh, namun pemerintah Aceh tidak dapat berbuat banyak bila pusat belum memberi “restu” terkait kepastian pelaksanaan Pilkada Aceh.
Harus diakui, peranan pusat dalam pelaksanaan Pilkada memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Terlebih di era rezim pilkada serentak seperti saat ini.
Keterlibatan Peran pusat dalam pelaksanaan pilkada cukup vital, seperti mengeluarkan pedoman penggunaan anggaran, evaluasi anggaran, mengatur hari libur nasional, penetapan Pj kepala daerah, pengangkatan kepala daerah hingga mengatur pelantikan kepala daerah terpilih.
Terlepas dari pasang surut kepastian pelaksanaan Pilkada Aceh, timbul pertanyaan mengapa sejumlah pihak terus mendesak agar Aceh harus menggelar Pilkada pada tahun 2022? Apakah karena semata ketentuan siklus pilkada lima tahunan telah tercantum dalam pasal 65 UUPA ataukah karena hal lainnya.
Penulis ingin mengajak semua pihak untuk membuka kembali lembaran sejarah proses demokratisasi Aceh. Sebab dari sinilah akan diketahui, bahwa pilkada Aceh sejak awal memang berbeda atau spesial dari wilayah lain di Indonesia.
Baca juga: Terkait Penasehat Khusus Gubernur Aceh, Ketua KIA: Data Pensus Bersifat Terbuka
Pilkada Sebagai Instrumen Penguatan Perdamaian Aceh
Sekilas Pilkada merupakan rutinitas demokrasi lima tahunan dalam rangka pergantian siklus kepemimpinan di tataran lokal. Namun untuk konteks Aceh memiliki keistimewaan dibanding daerah lain. Disatu sisi pemilu dan pilkada membuka ruang kompetisi yang sangat lebar antara elit politik.
Akan tetapi disisi lain -dalam konteks Aceh- pemilu dan khususnya Pilkada merupakan fondasi penting bagi penguatan perdamaian sekaligus menjaga iklim demokratisasi di Aceh terus berlanjut.
Hal ini tidak dapat dilepaskan dari akar histori perdamaian Aceh. Enam belas tahun lalu, tepatnya pada tanggal 15 agustus 2005, terjadi kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menghentikan konfik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.
Komitmen perdamaian tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helskinki. Harus disadari, bahwa perdamaian Aceh diperoleh dari serangkaian konflik penuh tumpah darah disertai dengan klimaks rumitnya proses perundingan antara pihak GAM dan Republik Indonesia.
Meski demikian, para pihak menyadari bahwa perdamaian adalah satu -satunya opsi bermartabat untuk mengatasi konflik Aceh dibandingkan dengan jalur kekerasan. Maka itu kemudian masa transisi Perdamaian Aceh dilanjutkan dengan sejumlah kebijakan dalam rangka menjamin perdamaian berkelanjutan.
Meliputi proses demiliterisasi (pelucutan senjata dan pembubaran gerilyawan bersenjata), pemenuhan hak-hak dasar, pemilihan umum yang demokratis dan konsep pemerintahan- sendiri (self government) yang kemudian diwujudkan melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Perdamaian membuka momentum bagi transformasi perjuangan eks kombatan. Dari sebelumnya perjuangan melalui peluru menjadi perjuangan melalui kotak suara (from bullet to ballot).
Transformasi perjuangan melalui jalur demokrasi dinilai sebagai salah satu faktor kunci mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kesepakatan damai.
Pemerintah pusat dibawah rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu meyakini bahwa demi menghindari kembalinya perjuangan bersenjata, faktor terpenting dalam mempertahankan perdamaian adalah melalui penempatan para bekas eks kombatan pada jabatan kunci di pemerintahan lokal.
Satu satunya jalur yang legal dan demokratis adalah melalui jalur pemilihan umum dan pilkada.
Harus disadari bahwa sejak awal, pelaksanaan pemilu dan Pilkada Aceh memang didesain tidak sama atau berbeda dengan wilayah lain di indonesia.
Tata kelola pemilu dan Pilkada di Aceh tidak didesain mengikuti mekanisme nasional namun memiliki keunikan sebagai pembeda dari wilayah lain yang bukan wilayah paska konflik. Terdapat perlakuan khas atau berbeda yang diterapkan pemerintah pusat dalam menjalankan proses transformasi politik di Aceh.
Perbedaan tersebut adalah proses demokrasi Aceh yang sarat dengan nilai nilai dalam perjanjian damai Helsinki, yaitu proses demokratisasi yang inklusif melelalui kesetaraan politik, yang menjamin sepenuhnya kebebasan sipil dan politik, serta hak berpartisipasi dalam Pemilu dengan mengajukan calon independen dan mendirikan partai politik lokal bagi seluruh rakyat Aceh tanpa memandang statusnya sebagai eks kombatan.
Desain kelembagaan penyelenggara pemilu juga unik. Mulai dari komposisi keanggotaan di tingkat provinsi sebanyak tujuh orang dan Kabupaten/kota lima orang (provinsi lain berbeda beda tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk) hingga proses seleksi yang melibatkan parlemen lokal (DPRA/DPRK).
Meski demikian, kemandirian lembaga tetap terjaga karena Komisi Independen Pemilihan sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Aceh tetap tunduk dan bekerja dibawah dibawah kontrol dan pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
Berangkat dari histori perdamaian Aceh, maka semua pihak kiranya perlu memiliki paradigma perdamaian terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada Aceh. Pemilu dan Pilkada Aceh tidak sama dengan wilayah lain di Indonesia yang tidak memiliki akar histori konflik puluhan tahun seperti Aceh.
Semua pihak perlu kembali membuka cakrawala dengan menempatkan pemilu dan pilkada Aceh tidak semata rutinitas demokrasi belaka, namun lebih penting daripada itu, terjaganya iklim demokratisasi di Aceh merupakan elemen vital bagi kestabilan keamanan dan keberlanjutan perdamaian abadi di Aceh.
Tanpa adanya paradigma perdamaian, maka potensi konflik dan ketidakstabilan keamanan dapat kembali terbuka lebar di Aceh. Ujung ujungnya hal demikian dapat saja mengancam perdamaian itu sendiri. Duh! []
Penulis adalah Peneliti Pemilu dan Demokrasi. Alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Konsentrasi Tata Kelola Pemilu