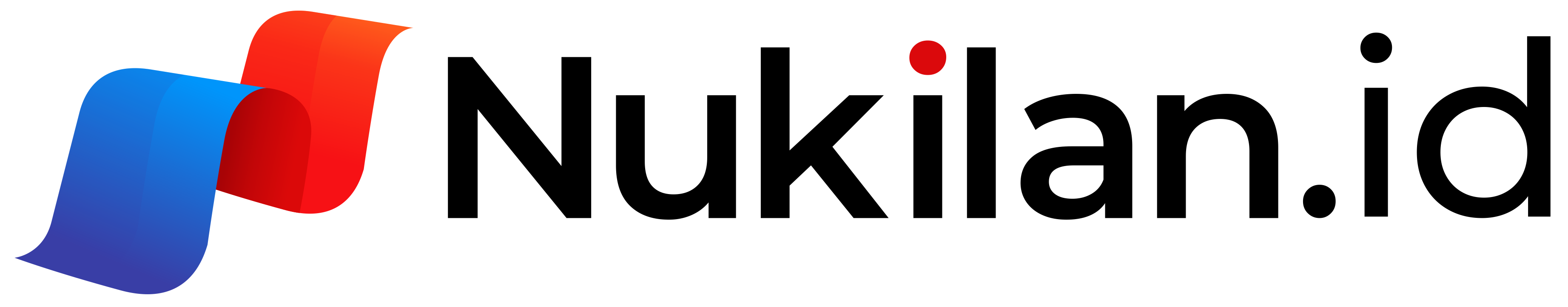NUKILAN.ID | Jakarta – Belakangan ini, dunia musik Indonesia tengah diguncang polemik besar mengenai royalti. Persoalan ini tidak hanya berkutat pada angka-angka, tetapi juga menyentuh isu mendasar: keadilan bagi para pencipta lagu yang karyanya menjadi tulang punggung industri hiburan.
Ketidakjelasan alur pembayaran royalti menciptakan benturan antara penyanyi, pencipta lagu, lembaga manajemen kolektif, hingga pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik. Musisi, masyarakat, dan pengusaha seolah-olah diposisikan berhadap-hadapan, sementara pemerintah dianggap hanya menjadi penonton.
Kisruh ini mengemuka setelah sejumlah penyanyi papan atas digugat karena membawakan lagu tanpa izin langsung dari penciptanya. Salah satu kasus mencolok adalah gugatan Kenan Nasution terhadap Vidi Aldiano. Kenan menuntut Rp24,5 miliar karena lagu “Nuansa Bening” dinyanyikan sebanyak 31 kali dalam kurun 16 tahun. Kasus serupa menimpa Agnes Monica yang diwajibkan membayar Rp1,5 miliar karena membawakan lagu “Bilang Saja” di tiga konser.
Bahkan, penyanyi dangdut Lesti Kejora pernah dilaporkan pidana karena mengunggah empat cover lagu ciptaan Yoni Dores di YouTube tanpa izin. Ia terancam hukuman hingga empat tahun penjara atau denda Rp1 miliar. Kasus-kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan luas: siapa sebenarnya yang paling berhak atas keuntungan dari sebuah karya musik?
Dari Mie Gacoan hingga Kafe Sunyi
Kasus yang paling menggegerkan publik beberapa bulan terakhir adalah sengketa antara restoran Mie Gacoan di Bali dengan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sengketa ini berakhir damai setelah pihak Mie Gacoan membayar royalti sebesar Rp2,2 miliar.
Namun pertanyaan besar pun muncul: mengapa ruang publik yang memutar lagu-lagu wajib membayar royalti, padahal musik tersebut sudah dibeli dari produser atau platform digital yang seharusnya juga membayar royalti kepada pencipta?
Kejadian ini membuat banyak pelaku usaha cemas. Beberapa kafe bahkan memilih meniadakan musik agar terhindar dari risiko hukum. Kondisi ini menimbulkan ironi: ruang publik yang biasanya semarak dengan musik berubah hening karena ketidakjelasan regulasi.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengatakan kebingungan itu muncul dari kurangnya sosialisasi.
“Padahal aturannya tidak demikian. Ini yang belum dipahami oleh semua pelaku usaha. Pemerintah harus jelas melakukan sosialisasinya agar tidak ada banyak persepsi yang ujung-ujungnya malah pidana,” katanya, dikutip BBC Indonesia, Kamis (7/8/2025).
Secara regulasi, pembayaran royalti sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
Dalam PP tersebut, terdapat 14 bentuk layanan publik yang dianggap komersial dan wajib membayar royalti. Mulai dari restoran, kafe, konser musik, hotel, hingga bioskop. Sistem yang digunakan adalah sistem blanket, yakni tarif tetap untuk memutar seluruh katalog musik yang dilindungi selama setahun penuh.
Meski begitu, praktik di lapangan sering memunculkan masalah. Tarif yang dihitung berdasarkan jumlah kursi atau kamar hotel dianggap tidak adil. Ketua PHRI Bali, Cok Ace, menilai aturan ini timpang karena menyamakan warteg dengan restoran fine dining.
“Kelihatannya harganya sama, pungutan per kursinya dihitungnya sama, tapi produk yang dia jual dan penghasilannya berbeda. Ini harusnya juga ada perbedaan. Jangan sampai warteg semua tipe dan restoran bintang lima sama kenanya,” kata Cok Ace, dikutip Tirto, Jumat (15/8/2025).
LMKN di Tengah Sorotan
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibentuk pada 2014 untuk menghimpun dan menyalurkan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait. LMKN terdiri dari dua bagian: LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait.
Namun belakangan, lembaga ini menghadapi kritik keras karena dianggap tidak transparan. Banyak musisi mengaku hanya mendapat royalti dalam jumlah kecil, jauh dari ekspektasi. Praktisi hukum Deolipa Yumara bahkan menuntut audit menyeluruh terhadap LMKN.
“Banyak pencipta lagu teriak cuma dapat Rp700 ribu setahun, ada juga yang Rp200 ribu. Padahal LMKN nagih hampir ke semua sektor hiburan,” ujar Deolipa, dikutip Kompas, Selasa (19/8/2025).
Kritik serupa juga datang dari penyanyi sekaligus dokter, Tompi, yang memilih mundur dari Wahana Musik Indonesia (WAMI) karena kecewa terhadap tata kelola royalti. Keputusan Tompi memicu diskusi publik soal perlunya transparansi yang lebih ketat.
Dampak ke Dunia Usaha
Polemik royalti bukan hanya soal hubungan antara musisi dan penyanyi, melainkan juga menyentuh dunia usaha. Salah seorang pemilik kafe di kawasan Lamnyong, Banda Aceh, Malik Akmal, menyebut penerapan royalti musik tidak masuk akal bagi pelaku usaha kecil.
Menurutnya, musik merupakan hiburan publik yang seharusnya bisa diakses secara bebas. Ia menilai pemberlakuan royalti untuk pemutaran musik di warung kopi atau kafe justru menyalahi fungsi utama musik sebagai sarana hiburan masyarakat.
“Masalah royalti nggak masuk akal menurut saya, karena musik diciptakan buat kita dengar. Kalau misalkan apa yang kita dengar harus bayar, aneh juga kebijakan negara seperti itu,” ujarnya kepada Nukilan, Kamis (21/8/2025).
Malik menjelaskan, perbedaan antara konser dengan pemutaran musik di warung kopi sangat jelas. Dalam konser, penonton memang membayar tiket karena ada biaya besar yang dikeluarkan penyelenggara. Namun, dalam usaha kecil seperti kafe, musik hanya sekadar pelengkap suasana.
Karena itu, menurutnya tidak tepat jika pemerintah membebankan royalti kepada pelaku UMKM. Ia juga menilai kebijakan ini akan memberatkan konsumen yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya daya tarik kafe dan warung kopi.
Banyak hotel dan restoran memilih menghentikan pemutaran musik demi menghindari tagihan yang dianggap memberatkan. Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengakui langkah itu diambil untuk menghindari masalah hukum.
“Untuk sementara ini, ada imbauan dari PHRI untuk tidak menyetel lagu-lagu atau mengadakan hiburan jika belum atau tidak membayar royalti. Mulai tidak memutar musik,” ujarnya kepada Kumparan, Senin (18/8/2025).
Di Bali, sejumlah hotel bahkan beralih menggunakan alat musik tradisional seperti rindik untuk mengisi suasana.
Kasus unik muncul di Pranaya Boutique Hotel, Tangerang Selatan, yang mendapat tagihan royalti padahal mereka hanya memelihara burung asli sebagai hiburan.
“Kalau menuduh, harus buktikan dulu. Jangan hanya main tembak. Harus jelas, lagu apa, musik apa, dan kapan itu diputar,” kata General Manager hotel, Bustamar Koto, dikutip Kompas, Jumat (15/8/2025).
Pengamat bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Fakhrurrazi, menilai rencana pemerintah untuk menerapkan royalti musik kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha, tidak wajar dan berpotensi menambah beban UMKM.
Menurutnya, masyarakat selama ini sudah berkontribusi terhadap industri musik melalui layanan berbayar. Fakhrurrazi menekankan bahwa ketika seseorang menggunakan aplikasi streaming seperti Apple Music, Spotify, atau Joox, sebenarnya mereka sudah membayar biaya lisensi untuk mendengarkan musik. Karena itu, jika pemerintah kembali membebankan royalti, maka hal tersebut dianggap sebagai pungutan ganda yang tidak masuk akal.
“Iya maksudnya nggak wajar aja pemerintah mencoba untuk menarik royalti dari masyarakat, jadi pemerintah itu zalim. Karena masalah hak cipta itu kita sudah beli streaming, masyarakat ada beli streaming, kenapa kena lagi. Apple Music, Spotify, Joox, itu kan sewa, kenapa kena lagi, maksudnya itu apa,” ujarnya kepada Nukilan, Kamis (21/8/2025).
Ia menilai, masyarakat pada dasarnya tidak keberatan jika hak cipta musisi dilindungi, namun mekanisme yang diambil pemerintah tidak boleh memberatkan konsumen dan pelaku usaha kecil.
Dalam pandangannya, kebijakan ini lebih terkesan mencari keuntungan tambahan dari publik, alih-alih memberikan perlindungan yang adil kepada para pencipta karya.
Ketua Umum Backstagers Indonesia Event Management Association, Andro Rohmana, menilai penerapan royalti 2 persen pada acara pernikahan adalah kesalahan fatal.
“Pernikahan bukan konser musik komersial, dan penerapan royalti 2 persen pada acara personal seperti pernikahan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, jadi tolong sudahi akrobat-akrobatnya,” tegasnya dalam siaran pers, dilansir Antara, Jumat (15/8/2025).
Dari kalangan pengusaha hiburan, Ketua Hiperhu Surabaya, George Hadiwiyanto, menyoroti ketidaktransparanan dalam distribusi dana royalti.
“Kami sepakat bahwa pencipta lagu wajib mendapat haknya. Tapi kenyataannya, banyak musisi hanya menerima royalti dalam jumlah kecil, sementara tagihan ke pelaku usaha sangat besar dan tak jelas dasar perhitungannya,” katanya, dikutip iNews, Kamis (14/8/2025).
Sorotan publik akhirnya membuat pemerintah turun tangan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemutaran musik di kafe dan ruang publik komersial memang wajib membayar royalti. Namun ia memastikan acara pernikahan dan kegiatan non-komersial bebas dari kewajiban itu.
“Nggak ada, kalau acara pernikahan nggak ada,” ujarnya, dilansir Antara, Senin (18/8/2025).
Supratman juga menekankan bahwa penerapan aturan tidak boleh membebani UMKM. Ia berencana mengaudit LMK dan LMKN untuk memastikan transparansi.
“Khusus royalti, ini lagi mau kami kumpulkan LMKN dan LMK-nya. Kami akan minta supaya akan ada audit, baik LMK-nya maupun LMKN-nya,” katanya, dikutip Republika, Senin (18/8/2025).
Di parlemen, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai praktik penarikan royalti selama ini “di luar kewajaran”. Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengkritik wacana penarikan royalti di pesta pernikahan yang ia sebut “sudah ngaco”.
Komisi XIII DPR bahkan berencana memanggil LMKN, Menteri Hukum, dan Menteri Kebudayaan untuk rapat khusus membahas polemik ini.
Menuju Sistem yang Lebih Adil
Sejumlah pihak menyarankan agar Indonesia mengadopsi sistem hybrid, yakni kombinasi lisensi kolektif melalui LMKN dan pembayaran langsung ke pencipta. Model ini dianggap lebih fleksibel dan dapat mengurangi ketegangan antara musisi, penyanyi, dan pelaku usaha.
Desakan juga datang dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu yang meminta pemerintah merevisi aturan royalti agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Once Mekel, penyanyi yang kini duduk sebagai anggota DPR RI, juga menekankan pentingnya perlindungan bagi UMKM.
“Iya saya kira kalau usaha-usaha kecil tidak usahlah, kan mereka sedang tumbuh dan tidak boleh diganggu dulu dengan masalah-masalah begini,” ujarnya, dikutip Bisnis, Sabtu (16/8/2025).
Polemik royalti musik di Indonesia telah membuka tabir persoalan mendasar: bagaimana negara melindungi hak pencipta tanpa menekan ruang usaha dan publik. Regulasi memang telah hadir melalui PP 56/2021, tetapi penerapannya menunjukkan bahwa aturan hukum tidak serta-merta bisa menyelesaikan masalah yang kompleks.
Di balik niat baik melindungi hak cipta, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Minimnya sosialisasi membuat banyak pelaku usaha kebingungan, sementara perbedaan persepsi tentang apa yang disebut “penggunaan komersial musik” melahirkan ketegangan. Dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana royalti juga semakin mengikis kepercayaan publik.
Bagi para musisi, royalti bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan soal keberlangsungan hidup. Di tengah dunia hiburan yang penuh ketidakpastian, royalti dipandang sebagai bentuk penghargaan paling konkret atas kerja kreatif yang sering kali lahir dengan perjuangan panjang.
Sebaliknya, bagi pelaku usaha, kewajiban ini bukan sekadar soal menghargai seni, tetapi menyangkut biaya operasional, margin keuntungan yang makin tipis, dan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis. Di satu sisi ada tuntutan etika untuk menghargai karya, di sisi lain ada tekanan ekonomi yang tidak bisa diabaikan.
Sementara bagi publik, polemik ini justru menimbulkan pertanyaan sederhana: mengapa mendengarkan musik di ruang publik bisa menjadi sesuatu yang rumit? Apakah setiap lagu yang diputar di restoran, kafe, atau hotel memang harus dibebani perhitungan ekonomi yang kaku? Pertanyaan ini menyentuh ranah lebih dalam, yakni bagaimana masyarakat Indonesia memandang musik itu sendiri: sebagai seni, sebagai hiburan, atau sebagai komoditas.
Jika tidak ditangani dengan transparansi dan mekanisme yang adil, kebijakan royalti justru berisiko menimbulkan jurang baru antara pencipta, pelaku usaha, dan publik. Alih-alih memperkuat penghargaan terhadap karya musik, kebijakan yang kabur dan sulit diakses justru bisa melahirkan resistensi, bahkan antipati.
Ke depan, pemerintah dituntut untuk menghadirkan sistem yang lebih sederhana, terukur, serta berbasis pada prinsip keterbukaan. Data penghimpunan dan distribusi royalti perlu tersedia secara publik, mekanisme penghitungan harus jelas, dan ruang dialog dengan pelaku usaha harus diperluas.
Dalam jangka panjang, isu royalti ini akan menentukan arah ekosistem musik Indonesia. Jika dikelola dengan benar, regulasi bisa menjadi fondasi baru bagi profesi pencipta lagu agar lebih sejahtera dan termotivasi melahirkan karya-karya bermutu.
Namun, jika dibiarkan berlarut tanpa kepastian, bukan tidak mungkin justru muncul gelombang perlawanan: pelaku usaha enggan memutar musik berlisensi, pencipta lagu kehilangan kepercayaan pada negara, dan publik semakin menjauh dari wacana apresiasi seni. Di titik ini, musik yang seharusnya mempersatukan justru berisiko menjadi pemicu friksi sosial.
Di era digital, arah polemik ini juga bisa berubah wajah. Meningkatnya penggunaan platform streaming dan algoritma musik berbasis data bisa memperbesar ketimpangan, jika regulasi nasional tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi global.
Generasi muda yang tumbuh bersama Spotify, YouTube, atau TikTok, mungkin memandang isu royalti sebagai sesuatu yang kuno jika tidak disertai dengan inovasi dalam pengelolaan. Indonesia berhadapan dengan pilihan: menjadikan regulasi royalti sebagai batu loncatan menuju ekosistem musik modern yang adil dan transparan, atau terjebak dalam konflik yang membuat industri berjalan di tempat.
Pada akhirnya, pertarungan kepentingan ini bukan hanya soal hukum dan ekonomi, tetapi juga soal bagaimana bangsa ini menempatkan seni dalam kehidupan bersama: sebagai hak yang harus dilindungi, sebagai ruang usaha yang harus didukung, sekaligus sebagai bagian dari kebudayaan yang seharusnya mempersatukan, bukan memecah belah.
Musik, dengan segala kekuatannya, seharusnya tetap menjadi ruang harmoni. Dan justru di titik persilangan kepentingan inilah, negara ditantang untuk benar-benar menghadirkan nada yang selaras, bukan sekadar regulasi yang menghasilkan “nada sumbang” yang berisik. []
Reporter: Sammy