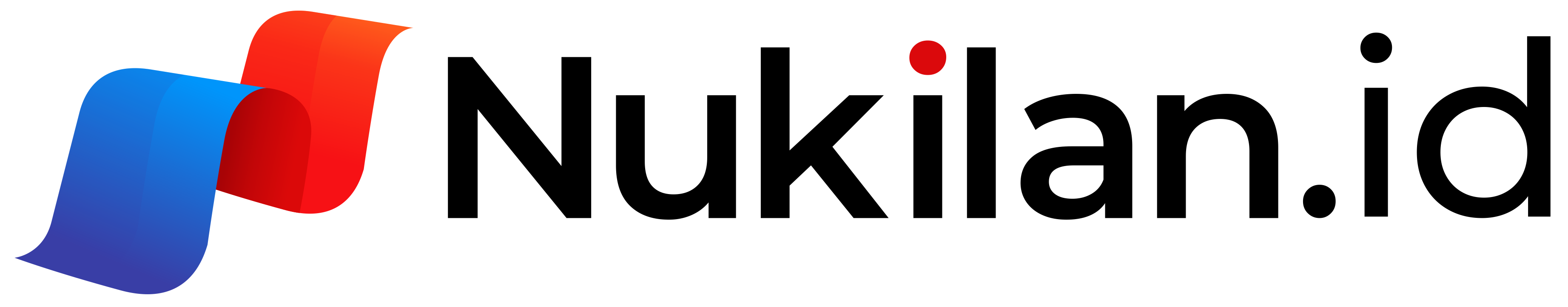NUKILAN.ID | OPINI — Kebebasan berekspresi adalah hak dasar setiap manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ia adalah napas demokrasi, ruang bagi warga untuk menyuarakan pikiran tanpa rasa takut. Namun, di Aceh, hak ini sering berjalan di jalan yang berliku: antara semangat menegakkan syariat, menjaga adat, dan menghidupkan demokrasi yang sehat.
Sebagai provinsi dengan kekhususan dan otonomi khusus, Aceh kerap menjadi sorotan dalam soal kebebasan sipil. Di satu sisi, masyarakatnya dikenal kritis dan aktif dalam wacana publik; di sisi lain, ada dinding sosial dan kultural yang kadang membatasi ruang itu sendiri. Pertanyaannya: seberapa bebas warga Aceh bisa mengekspresikan pendapat mereka hari ini?
Tidak sedikit modal sosial yang dimiliki Aceh untuk mengembangkan ruang ekspresi yang sehat. Sejarah panjang perjuangan, tradisi musyawarah dalam adat, dan kuatnya lembaga-lembaga keagamaan semestinya bisa menjadi fondasi bagi dialog terbuka yang beradab.
Dalam beberapa tahun terakhir, upaya memperkuat norma kebebasan berekspresi mulai tampak. Komnas HAM, misalnya, pada Agustus 2024 menggelar diskusi publik dan diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 Tahun 2021 di Banda Aceh — membahas pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di daerah bersyariat. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa hak berekspresi harus diatur, bukan dibatasi.
Penelitian juga menunjukkan korelasi positif antara kebebasan berekspresi, akses informasi, dan partisipasi politik masyarakat. Ketika warga berani bersuara, partisipasi mereka dalam demokrasi meningkat. Dalam konteks Aceh, ini berarti peluang bagi masyarakat untuk ikut menentukan arah pembangunan dan menegakkan keadilan sosial.
Namun, potensi itu masih tertahan oleh sejumlah kendala nyata. Salah satunya adalah persoalan regulasi dan tafsir hukum.
Secara nasional, laporan Komnas HAM mencatat pelanggaran kebebasan berpendapat di ruang digital terus meningkat. UU ITE masih sering digunakan sebagai alat untuk membungkam suara kritis, baik terhadap pemerintah maupun lembaga agama. Di Aceh, tekanan itu berlipat: selain berhadapan dengan hukum nasional, ekspresi warga juga dinilai melalui kacamata syariat dan norma adat yang ketat.
Kondisi ini membuat banyak orang memilih diam. Di media sosial, misalnya, topik-topik yang dianggap “sensitif” seperti pluralisme, gender, atau kritik terhadap kebijakan dayah jarang sekali muncul dari akun-akun Aceh. Ketakutan terhadap sanksi sosial, laporan ke pihak berwenang, atau bahkan stigma masyarakat membuat ruang publik digital menjadi sempit.
Masalah lain adalah kurangnya perlindungan terhadap jurnalis dan aktivis. Sejumlah media lokal mengaku sering menghadapi tekanan ketika memberitakan isu-isu kontroversial, terutama yang berkaitan dengan pejabat, proyek publik, atau pelanggaran syariat. Padahal, kebebasan pers adalah bagian integral dari kebebasan berekspresi. Serangan terhadap jurnalis sama saja dengan serangan terhadap hak publik untuk tahu.
Dilema terbesar di Aceh terletak pada upaya menyeimbangkan antara penerapan syariat Islam dengan penghormatan terhadap hak-hak sipil.
Sebagai masyarakat yang religius, wajar jika norma-norma moral dijunjung tinggi. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika norma itu berubah menjadi alat pembatas. Misalnya, pandangan bahwa kritik terhadap kebijakan keagamaan dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap agama. Padahal, kritik dan perbedaan pendapat justru bagian dari dinamika intelektual dalam Islam itu sendiri.
Ulama-ulama klasik seperti Imam Syafi’i dan Al-Ghazali menekankan pentingnya ikhtilaf atau perbedaan pendapat, sebagai tanda kehidupan ilmu. Aceh seharusnya bisa menjadi contoh bagaimana syariat dan kebebasan berpikir berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.
Jika ruang kritik dibungkam atas nama menjaga moral, kita justru kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Demokrasi tanpa kritik adalah ruang hampa. Dalam konteks Aceh, menjaga marwah agama tidak berarti menutup telinga terhadap suara rakyat.
Lebih jauh dari sekadar hukum dan regulasi, tantangan terbesar kebebasan berekspresi di Aceh adalah soal budaya. Budaya kita belum sepenuhnya siap menerima perbedaan.
Dalam banyak forum publik, kritik sering dianggap sebagai bentuk perlawanan, bukan masukan. Di media sosial, pendapat yang sedikit berbeda bisa dengan cepat dihakimi. Di kampus, mahasiswa yang vokal kerap dicap sebagai pembangkang. Padahal, dari sinilah seharusnya lahir ruang pembelajaran tentang toleransi, debat sehat, dan penghargaan terhadap pandangan lain.
Budaya dialog ini perlu dibangun sejak dini, melalui pendidikan dan literasi publik. Masyarakat harus diajak memahami perbedaan antara kritik dan ujaran kebencian, antara menyampaikan pendapat dan menghina. Tanpa pemahaman itu, kebebasan akan selalu disalahartikan, entah menjadi kebablasan atau malah dimatikan.
Kebebasan berekspresi bukan berarti tanpa batas. Namun batas itu seharusnya adil, jelas, dan proporsional. Dalam konteks Aceh, batasan berbasis syariat dan adat memang penting, tetapi perlu dijelaskan secara transparan agar warga tahu di mana garisnya.
Saya percaya, ada jalan tengah antara menjaga moral publik dan menghormati hak asasi manusia. Jalan tengah itu adalah dialog, ruang di mana semua pihak bisa duduk bersama, mendengarkan, dan mencari titik temu.
Pemerintah Aceh bersama Majelis Adat Aceh, ulama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil seharusnya mulai merumuskan pedoman lokal kebebasan berekspresi yang berpijak pada nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, tapi juga menghormati konstitusi dan standar HAM internasional.
Selain itu, perlu dibentuk lembaga pengaduan independen di Aceh untuk menampung kasus pelanggaran kebebasan berekspresi, baik di dunia nyata maupun digital. Perlindungan terhadap jurnalis, seniman, dan aktivis harus dijamin secara hukum agar mereka tidak lagi menjadi korban ketakutan.
Pendidikan publik pun tak kalah penting. Literasi digital dan literasi media harus diperluas, terutama di kalangan muda. Mereka harus belajar bagaimana menyampaikan kritik dengan santun, dan di saat yang sama memahami batas etika dalam berekspresi.
Kebebasan berekspresi di Aceh berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada keinginan kuat untuk menjaga moralitas masyarakat; di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk membuka ruang kritik dan kreativitas.
Aceh telah melewati sejarah panjang konflik dan perdamaian. Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa perdamaian itu diisi dengan ruang berpikir yang bebas, sehat, dan produktif. Karena pada akhirnya, masyarakat yang berani berbicara adalah masyarakat yang berani maju.
Seperti kata Pramoedya Ananta Toer dari bukunya Rumah Kaca, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat.” Di Aceh, barangkali waktunya kita tambahkan satu kalimat: orang boleh beriman sedalam lautan, tapi selama ia tak berani bersuara, ia akan tenggelam dalam diamnya sendiri. (XRQ)
Penulis: Akil