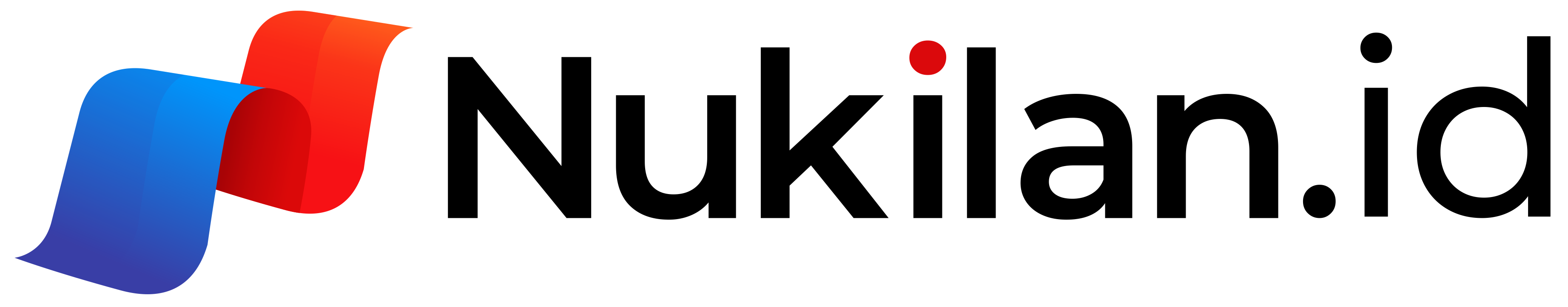NUKILAN.ID | OPINI – Perjanjian Damai Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 menandai babak baru bagi Aceh, mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah melanda provinsi ini selama puluhan tahun.
Era perdamaian ini membawa serta harapan besar akan pembangunan, pemulihan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik optimisme tersebut, Aceh juga dihadapkan pada tantangan serius yang tak kalah kompleks, yaitu isu kerusakan lingkungan.
Konflik bersenjata, meskipun telah usai, meninggalkan jejak yang mendalam pada ekosistem Aceh, dan proses pembangunan pasca-damai, jika tidak dikelola dengan bijak, berpotensi memperparah kondisi lingkungan yang sudah rentan.
Deforestasi: Ancaman Senyap di Balik Perdamaian
Perdamaian di Aceh, alih-alih membawa pemulihan bagi hutan, justru diiringi dengan laju deforestasi yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, hilangnya tutupan hutan di Aceh telah menjadi pemicu berantai yang mempercepat degradasi lingkungan dan memperparah frekuensi bencana alam.
Pada periode awal pasca-damai, yaitu antara tahun 2005 hingga 2006, setidaknya 266.000 hektare hutan di Provinsi Aceh mengalami kerusakan berat. Angka ini menunjukkan betapa cepatnya kerusakan hutan terjadi bahkan di tahun-tahun pertama setelah konflik berakhir. Tren ini terus berlanjut.
Selama lima tahun, Aceh kehilangan tutupan hutan hingga 71.552 hektare, yang berpotensi memicu bencana alam. Secara lebih luas, dari tahun 2001 hingga 2024, Aceh telah kehilangan 857 ribu hektare tutupan pohon, setara dengan 17% dari total luas tutupan pohon pada tahun 2000.
Penyebab utama deforestasi di Aceh sangat kompleks dan saling terkait. Salah satu faktor dominan adalah aktivitas illegal logging yang marak terjadi, seringkali didorong oleh permintaan pasar gelap dan lemahnya penegakan hukum.
Selain itu, ekspansi perkebunan, terutama kelapa sawit, menjadi pendorong utama lainnya. Pembukaan lahan untuk perkebunan skala besar seringkali dilakukan dengan mengorbankan kawasan hutan primer yang kaya keanekaragaman hayati.
Dampak dari deforestasi ini sangat nyata dan merugikan. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor menjadi konsekuensi langsung dari hilangnya tutupan hutan.
Perubahan iklim lokal juga terjadi, dengan peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan yang berdampak pada sektor pertanian dan kehidupan masyarakat.
Pencemaran Lingkungan: Beban yang Terus Bertambah
Selain deforestasi, masalah pencemaran lingkungan juga menjadi beban serius bagi Aceh di masa perdamaian. Berbagai jenis pencemaran, mulai dari logam berat hingga sampah, terus mengancam kesehatan ekosistem dan masyarakat.
Pasca-tsunami pada tahun 2004, Aceh dihadapkan pada masalah baru yang tak terduga. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan bahwa lima kabupaten di Aceh tercemar logam berat, sebuah kondisi yang sangat membahayakan. Pencemaran ini kemungkinan besar berasal dari material sisa tsunami atau aktivitas pasca-bencana yang tidak terkontrol.
Selain itu, seiring dengan kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih, kasus-kasus pencemaran lingkungan cenderung meningkat .
Aktivitas pertambangan, baik yang legal maupun ilegal, juga menjadi sumber pencemaran lingkungan yang signifikan. Pertambangan ilegal, khususnya, seringkali tidak memperhatikan standar lingkungan, menyebabkan kerusakan ekosistem dan pencemaran air serta tanah oleh limbah tambang . Meskipun ada upaya untuk mengatur dan mengendalikan, tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan masih sangat besar.
Dampak dari pencemaran lingkungan ini sangat luas. Kesehatan masyarakat menjadi taruhan utama, dengan potensi penyakit yang disebabkan oleh paparan logam berat, bakteri dari sampah, dan zat berbahaya lainnya.
Ekosistem air, seperti sungai dan laut, juga terancam, mengganggu kehidupan akuatik dan sumber daya perikanan yang menjadi mata pencaharian banyak masyarakat Aceh. Pencemaran tanah mengurangi kesuburan dan produktivitas lahan pertanian.
Selain deforestasi dan pencemaran, Aceh juga tidak luput dari dampak isu lingkungan global, terutama perubahan iklim. Meskipun bukan penyebab utama, perubahan iklim memperparah kerentanan ekosistem Aceh yang sudah tertekan.
Peningkatan suhu global dan perubahan pola curah hujan dapat memicu kekeringan di satu sisi dan banjir di sisi lain, mengancam sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.
Ekosistem pesisir Aceh, yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat dan keanekaragaman hayati laut, juga menghadapi degradasi. Meskipun data spesifik mengenai tingkat degradasi pasca-2005 tidak selalu tersedia secara terpusat, ancaman terhadap hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun terus ada.
Aktivitas penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, pembangunan di wilayah pesisir, dan dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan pengasaman laut, semuanya berkontribusi pada kerusakan ekosistem ini.
Kerusakan ekosistem pesisir tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan kerentanan wilayah pesisir terhadap bencana alam seperti abrasi dan gelombang pasang.
Tantangan dan Harapan
Perdamaian yang telah dinikmati Aceh sejak tahun 2005 adalah anugerah yang harus dijaga. Namun, di balik ketenangan pasca-konflik, lingkungan Aceh menghadapi tantangan serius yang tidak boleh diabaikan. Deforestasi yang masif dan pencemaran lingkungan yang terus meningkat menjadi bukti nyata bahwa pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat mengikis fondasi ekologis yang vital bagi kehidupan.
Menatap lingkungan Aceh di masa perdamaian berarti mengakui bahwa tantangan lingkungan yang ada sangatlah besar, namun juga menyadari adanya peluang untuk perubahan positif. Keberlanjutan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh elemen.
Menatap lingkungan Aceh di masa perdamaian adalah sebuah panggilan untuk bertindak. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, dan tanggung jawab dari sektor swasta untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam.
Penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, edukasi lingkungan, dan adopsi praktik pembangunan berkelanjutan adalah langkah-langkah krusial yang harus diambil. Hanya dengan upaya kolektif dan sinergi yang kuat, Aceh dapat memastikan bahwa perdamaian yang telah diraih tidak hanya membawa kemakmuran bagi manusianya, tetapi juga keberlanjutan bagi lingkungannya, demi generasi mendatang. [hrs]
Penulis: Haris