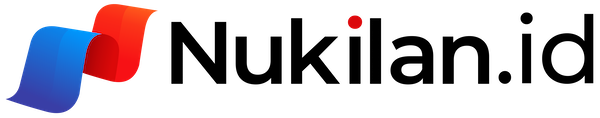Penulis: Masri Amin
Semasa kepemimpinan Presiden SBY, ia membuka wacana agar para gubernur tidak dipilih oleh rakyat melainkan ditentukan DPRD tingkat provinsi. Opsi lain: diangkat presiden.
Penolakan bergemuruh begitu kencang dengan beragam dalih. Presiden SBY punya rasionalitas yang cukup, namun dicurigai bagian dari pelanggengan kekuasaan saat itu. Akhirnya idenya tak dijalankan dan tenggelam demi menghargai aspirasi dan konsensus rakyat.
Kini, pada masa Presiden Jokowi, ide tersebut—walau telah dimodifikasi—diberi ruang oleh regulasi untuk konteks kursi kepala daerah yang akan kosong pada 2022-2023. Bukan cuma posisi gubernur, bupati dan wali kota juga akan ditentukan pejabatnya untuk mengisi masa jeda/transisi menuju Pilkada Serentak 2024. Ini sebuah realitas gila.
Dengan begitu, lebih dari separuh negeri ini akan dijabat oleh para pelaksana tugas yang legal tetapi bersifat “boneka”. Maksudnya, kedudukan mereka secara hukum memang sah tetapi secara politik akan menjadi alat jejaring kuasa negara. Dan legitimasi murni dari rakyat tak ada.
Potensi kegaduhan politik lokal akan jauh lebih parah sekiranya itu terjadi, karena hal ini terkait otoritas terbatas dan legitimasi “palsu”. Akan terjadi kekacauan pada mesin birokrasi secara meluas karena birokrasi dipakai untuk misi-misi politis atau non-pelayanan publik.
Terkait hal ini, ada paradoksial basis berpikir Presiden Jokowi dalam meredam revisi Undang-Undang 10/2016 yang memengaruhi sikap partai politik.
Presiden Jokowi memasukkan komponen energi yang diperlukan untuk menuntaskan Covid-19 dalam hal menolak pilkada 2022 dan 2023 namun mengabaikannya untuk pilkada 2020 yang lalu. Begitu juga alasan tidak menunda pilkada 2020 dengan mengumbar akan terlalu lama daerah dijabat Plt/Pj, namun menghilangkan alasan itu untuk Pilkada 2022 dan 2023.
Amnesia dan Krisis Moral Politik Berbangsa yang Dipanggungkan secara telanjang. Kasus sama namun sikap berbeda dalam rentang waktu pendek. Patut diduga punya tujuan untuk merawat oligarki, bancakan politik dan memancung “siklus” dan struktur politik secara “kurang etis”. Terlebih, Pemilu lebih dahulu beberapa bulan digelar, baru Pilkada. Artinya, potensi Pj/Plt KDH menjadi mesin politik ketika Pemilu menjadi kecurigaan yang mendasar. Belum lagi ditengarai variabel untuk menjegal jalan Anies Baswedan menghuni Balai Kota DKI untuk periode ke 2 tahun 2022 yang ditakuti menjadi peta Jalan Tol penghuni Istana Negara tahun 2024.
Konteks lokal Aceh turut berimbas sikap ambigu dari pusat kekuasaan Jakarta yang bertameng konsistensi. Partai Demokrat berkomitmen menjaga kekhususan Aceh yang termaktub dalam UU PA 11/2006 dengan mendukung Pilkada Aceh 2022. Bila jujur kita melihat, tidak murni menghargai kekhususan Aceh, tetapi terusan dan irisan sikap Demokrat yang mendukung Pilkada secara Periodik di 2022 dan 2023 secara nasional yang berbeda dengan ” niat” rezim Jokowi tahun 2024.
Karena menguntungkan, Aceh menghargai sikap Demokrat sebagai energi positif untuk mendorong Pilkada 2022 untuk Aceh. Sikap Demokrat cukup “cerdas” mengambil panggung di Aceh. Namun sikap Aceh (DPRA ) agak Kurang Cerdas mengambil energi secara politik mengunjungi Fraksi Demokrat secara Khusus diawal safari di Jakarta, tanpa mengunjungi secara khusus Fraksi atau faksi para pendukung Pilkada 2024 pada kesempatan Pertama agar setara (terpublis). Untuk harmonisasi dan energi politik lokal – tindakan ini bisa dimaklumi, karena Demokrat pemegang mandat power full Eksekutif di Aceh.
Sikap Demokrat Mendukung Pilkada 2022 di Aceh terlihat cukup jelas dan nyata, namun berbanding terbalik dengan tidak bersikap atas Jabatan Wakil Gubernur Aceh yang kosong. Sikap paradok ini bukan hanya diperankan Demokrat semata, namun turut diperankan partai pengusung lainnya serta lembaga DPRA. DPRA bersikukuh mengawal kekhususan Aceh lewat Pilkada 2022, namun bersikap cuek dan menelantarkan kursi Wagub yang kosong dengan membangun narasi dan dalih politik tersendiri. Jabatan Wagub itu ada dalam UUPA, Namun dibiarkan kosong berjelaga disudut ruang politik kekhususan Aceh.
Terlepas siapa yang mengisi kursi itu dan stategis atau tidak dalam rentang waktu yang tidak “seksi” lagi, bahwa Kursi Wagub itu wajib di isi. Bila tidak diisi, maka secara berjamaah, terutama di shaff terdepan para partai pengusung dan di ikuti DPRA turut membajak hak rakyat Aceh agar tidak dilayani oleh struktur politik negara dengan membiarkan kursi wagub kosong. Lebih dari itu, secara bersama-sama struktur politik telah menginjak dan merobek regulasi termasuk didalamnya UUPA yang diagungkan khusus. Ini sebuah pengkhianatan yang massif.
Sekali lagi ini semata suguhan panggung politik paradoks. Politik yang kita kenal dipenuhi sikap ambigu dan rendah nilai moral konsistensi. Bukan soal benci dan senang, kita atau lawan. Namun itulah dinamika politik yang diyakini umum tentang politik itu sendiri. Kita nikmati diruang dan waktu yang berbeda.
Masri Amin, alumnus Pascasarjana Ilmu Politik UGM